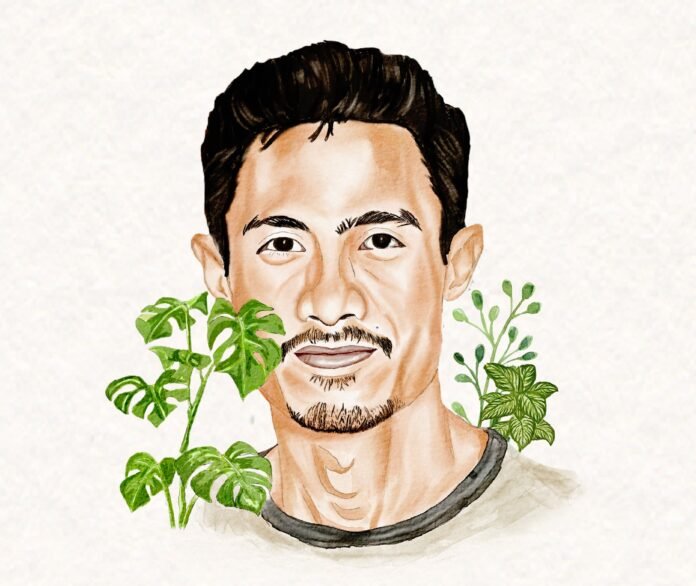“Setiap orang memiliki potensi pengetahuan, namun hanya sebagian yang memilih berperan aktif meletakkan pengetahuannya dalam spektrum ideologis perjuangan sosial. Sisanya adalah sampah sejarah yang hanyut dalam kenyamanan, jauh dari risiko dan realitas rakyat yang kian teralienasi.”
Dalam dekade terakhir, arus investasi global semakin terarah pada wilayah-wilayah yang selama ini dianggap “perifer“—termasuk di dalamnya kawasan Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Proses ini tak lepas dari logika kapitalisme global yang mencari sumber daya baru dan tenaga kerja murah demi mempertahankan akumulasi kapital. Di Indonesia, kita menyaksikan lonjakan investasi di sektor pertambangan, perkebunan skala besar, serta pembangunan infrastruktur strategis yang didukung negara. Fenomena ini menunjukkan wajah kapitalisme yang bersifat ekstraktif: mengeruk sumber daya alam dan menciptakan ketergantungan struktural bagi masyarakat lokal.
Namun, bersamaan dengan itu, gejala proletarisasi; yakni perubahan struktur sosial di mana petani, nelayan, dan pelaku ekonomi lokal kehilangan alat produksinya dan dipaksa masuk dalam relasi kerja upahan yang makin kentara. Situasi ini menyebabkan kemiskinan ekstrem yang bukan lagi bersifat insidental, tetapi sistemik.
Dalam sejarah, relasi antara ekspansi kapital dan gerakan perlawanan rakyat selalu bersifat dialektis. Ketika kapital memperluas hegemoninya, selalu muncul bentuk-bentuk resistensi dari mereka yang tereksklusi atau terpinggirkan. Perlawanan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk yang rapi dan terorganisir; ia bisa sporadis, acak, dan bahkan tampak kontradiktif. Namun dalam jangka panjang, muncul pola resistensi yang sistemik dan programatik, terutama ketika ada bentuk kepeloporan yang mampu menyatukan pengalaman kolektif rakyat dalam agenda politik yang jelas.
Kepeloporan semacam itu, sebagaimana dicatat oleh Antonio Gramsci dalam Prison Notebooks (1971), membutuhkan “intelektual organik”, yakni figur-figur yang berasal dari kelas rakyat dan memiliki kemampuan membangun artikulasi politik yang berakar pada pengalaman material rakyat. Kepemimpinan ini tidak bersifat elitis atau eksklusif, melainkan membumi dan membangun kesadaran kritis secara kolektif.
Negara dan korporasi tidak tinggal diam dalam menghadapi potensi perlawanan. Mereka secara sistematis membangun proyek moderasi kesadaran melalui pendidikan, media, wacana agama, dan budaya populer. Tujuannya sederhana: mengelola kemarahan agar tidak berubah menjadi tindakan politik. Pendidikan dipangkas dari semangat pembebasan menjadi sekadar reproduksi tenaga kerja; media lebih banyak memproduksi ketakutan dan konsumsi; agama dijadikan alat legitimasi ketertundukan, bukan pembebasan.
Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa arus kesadaran rakyat tak sepenuhnya bisa diredam. Di balik sikap diam, seringkali tersembunyi amarah yang menunggu momentum. Perlawanan bisa muncul dari konflik agraria, penolakan tambang, gerakan buruh, hingga komunitas adat yang mempertahankan ruang hidupnya. Dari berbagai fragmen inilah, kemungkinan lahirnya agenda politik progresif-populis dapat tumbuh.
Dalam konteks ini, kita menyaksikan satu ironi besar: kaum terdidik justru tidak menjadi bagian dari perubahan. Sebaliknya, mereka sering kali terjebak dalam posisi yang ambigu.
Sejarah intelektual kiri juga mencatat contoh paling gamblang dari pengkhianatan terhadap cita-cita emansipasi dalam sosok Karl Kautsky, seorang teoritikus besar Marxis Jerman yang pada awalnya dikenal sebagai “Paus Marxisme” namun kemudian justru menjadi simbol deformasi teori revolusioner menjadi reformisme yang jinak. Dalam polemiknya dengan Lenin pada awal abad ke-20, Kautsky memilih jalan kompromi dengan demokrasi borjuis, dan menolak revolusi proletariat sebagai jalan utama pembebasan. Ia mengabaikan realitas penindasan struktural yang dialami rakyat demi menjaga ilusi netralitas intelektual. Lenin dalam Revolusi Proletariat dan Kautsky Si Pengkhianat (1918) mengecam keras sikap ini sebagai bentuk pengkhianatan intelektual yang menyelubungi ketundukan terhadap tatanan kapitalis dengan retorika moral. Fenomena ini tidak jauh berbeda dengan banyak intelektual hari ini, yang mengedepankan posisi moderat, netral, dan “rasional” (kata mereka), padahal justru sedang menjadi alat hegemonik kelas berkuasa.
Sebaliknya, sejarah juga mencatat keberanian tokoh-tokoh seperti Rosa Luxemburg dan Leon Trotsky, yang tidak memisahkan intelektualitas dari praksis revolusioner. Luxemburg dalam Reformasi atau Revolusi (1900) dengan tajam mengkritik pendekatan reformis yang menjinakkan perjuangan kelas menjadi sekadar agenda kebijakan. Ia bersikukuh bahwa kesadaran kelas hanya bisa terbentuk melalui perjuangan konkret yang menentang struktur kapitalis. Trotsky, dalam Revolusi Permanen (1930), menegaskan bahwa intelektual yang berpihak pada rakyat harus hidup dalam arus revolusi, bukan bersembunyi dalam lembaga-lembaga yang nyaman. Keduanya mewariskan etos keberanian untuk berpikir dan bertindak dalam arah sejarah yang progresif, meski penuh risiko dan pengorbanan.
Mereka yang memilih berselingkuh dengan oligarki, dalam bentuk apa pun, jelas telah menjauhkan diri dari keberpihakan terhadap rakyat. Dalam lanskap politik hari ini yang semakin dikendalikan oleh logika oligarkis, pengetahuan yang mereka miliki tidak diartikulasikan ke dalam praksis transformatif. Alih-alih menjadi alat pembebasan, pengetahuan itu justru dirawat sebagai simbol eksklusivitas, dijaga dalam ruang-ruang ekslusif, simbolik dan akademik yang steril dari realitas. Mereka lebih memilih menjadi komentator yang nyaman dalam analisis, ketimbang pelaku perubahan yang berani mengambil risiko di medan perjuangan.
Sebagaimana diungkapkan oleh Paulo Freire dalam Pendidikan Kaum Tertindas (1970), pendidikan yang membebaskan seharusnya membangun kesadaran kritis (conscientizacao), bukan justru menciptakan alienasi. Kaum terdidik yang gagal menjadi bagian dari gerakan rakyat adalah manifestasi dari pendidikan yang tidak membebaskan. Ketika rakyat melawan kongsi negara-modal-senjata, mereka lebih sering diam, atau jika bicara, justru mereproduksi bahasa kekuasaan dalam bentuk yang lebih canggih dan membingungkan.
David Harvey (2014) juga mencatat bahwa salah satu kontradiksi kapitalisme saat ini adalah “kekosongan intelektual” di kalangan akademisi dan profesional muda. Mereka cenderung adaptif terhadap sistem, bukan kritis. Dalam keadaan ini, intelektual kehilangan keberanian untuk hidup dalam risiko dan lebih memilih kenyamanan institusional.
Perubahan sosial yang sejati membutuhkan keberanian untuk melawan arus, bukan sekadar kemampuan membaca situasi. Dalam hal ini, peran kaum intelektual harus dikembalikan pada misi historisnya: menjadi jembatan antara pengalaman rakyat dan agenda transformasi sosial. Kepeloporan progresif-populis tidak lahir dari seminar akademik atau jurnal ilmiah, tetapi dari keberanian untuk hidup bersama rakyat, mendengar mereka, dan bertindak bersamanya.
Dengan demikian, proyek politik ke depan bukan hanya soal mengganti aktor kekuasaan, tetapi membangun ulang relasi sosial-politik yang adil dan setara. Di sinilah peran intelektual, jika tak ingin menjadi tragis dan khianat, harus dijalankan dengan keberpihakan yang nyata, bukan sekadar wacana.
“Tidak ada transformasi sosial tanpa penderitaan, dan tidak ada intelektualitas sejati tanpa keberanian untuk hidup dalam risiko. Intelektual yang absen dalam perjuangan rakyat hanyalah catatan kaki dari sejarah yang dilupakan”.
SM Malaka